Karena hari ini hari lahir almarhum Ki Hadjar Dewantara, aku ingin mengunggah tulisan tentang kegelisahanku soal pendidikan, selakunya mahasiswa tua yang sedang mencoba kembali bersekolah.
Akhir tahun kemarin, aku memutuskan untuk mengambil program master. Tidak usah jauh-jauh, aku kuliah di sebuah universitas di kota tempat aku tinggal sekarang (Depok, friendly and religious city, ceunah). Tujuan aku sekolah lagi sederhana, aku sudah merasa bodoh karena hanya diam di rumah dan mengandalkan pekerjaan sebagai penulis lepas. Aku ingin punya aktivitas dan aku haus ilmu. Oke, sepik. Aku ingin ada nilai tambah di CV-ku.
Tua-tua sekolah. Mungkin itu gambaran yang tepat untuk situasiku saat ini. Teman-teman sebayaku yang sedang mengambil S2 atau S3 rata-rata memilih berkuliah di luar negeri. Sementara di sini, teman-teman sekelasku rata-rata berusia jauh lebih muda dari aku. Banyak dari mereka yang baru kelar mengambil gelar sarjana dan memutuskan untuk langsung melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kuhitung-hitung, dari total 60 orang, hanya ada empat orang yang lebih tua dariku.
Awalnya, aku merasa terintimidasi. Di mataku, mereka sangat pintar dan betul-betul fresh dengan ilmu yang sedang kami dalami. Otak mereka masih cepat menyerap apa yang diajarkan di kelas, sementara aku cuma bisa cengok dan mengejar ketertinggalan dengan begadang semalaman. Terakhir kali aku duduk di kelas adalah tahun 2010. Setelahnya, aku sibuk ngopi sambil mengejar deadline mencari uang di bidang yang agak nyeleneh dari ilmu yang kudalami selama S1. Agar tenang selama masa studiku ini, aku selalu mengingatkan diri sendiri: “Kamu di sini untuk belajar dan bukan berkompetisi. Yang perlu kamu kalahkan adalah dirimu sendiri.”
Well, that worked. For some time. Sampai akhirnya ada satu tradisi yang awalnya aku ikuti, tapi pada akhirnya mulai mengganggu. Setiap dari kami akan presentasi, kami selalu mengingatkan satu dan lainnya: “Jangan tanya, ya!”. Atau kalau kami diwajibkan bertanya pada presenter: “Nanyanya jangan banyak-banyak/susah-susah ya!”. Iya, aku juga sering memohon begitu pada teman-temanku. Namun, ada satu hal yang kemudian aku rasakan: aku kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak ilmu lewat diskusi.
Sampai akhirnya, masalah tanya jawab ini mulai menimbulkan bibit-bibit konflik di antara kami. Temanku marah karena aku menanyakan pertanyaan yang, dalam pembelaanku, membuatku sangat bersemangat dan penasaran dan dalam pembelaan temanku, menghancurkan presentasinya. Temanku yang lain pun bertengkar dengan temannya dengan alasan yang sama: pertanyaannya terlalu banyak dan terlalu menyerang.
Persoalan tanya-jawab ini akhirnya menggugah rasa penasaran ‘kawan serumahku’, sebut saja namanya Zaki, yang adalah namanya yang sebenar-benarnya. Zaki adalah teman diskusi dan teman berantemku, yang ketika isi kepalanya sedang agak waras, kerap membantu aku untuk merefleksikan kejadian-kejadian di sekitarku dengan bijaksana. Termasuk soal tanya-jawab ini.
Kurang lebih, begini isi pembicaraan kami yang sudah dirapihkan agar tidak mengandung makian dan diksinya diperhalus agar terkesan elegan:
Z: “Aku bingung dengan teman-temanmu. Mengapa mereka takut diberi pertanyaan ketika berada di depan kelas?”
A: “Mungkin mereka takut tidak bisa menjawab.”
Z: “Kenapa harus takut? Kenapa tidak bisa jujur mengatakan ‘saya tidak bisa menjawab’ dan meminta bantuan dosen?”
A: “Mungkin mereka takut bahwa itu akan membuat mereka terlihat bodoh dan mendapatkan nilai jelek. Paling tidak, itu yang aku rasakan.”
Z: “Lalu kalau begitu apa esensinya kelas buat belajar? Kalian berada di kelas buat belajar, bukan? Aku tidak nyaman melihatmu terjebak dalam tradisi ‘jangan tanya, please‘ ini…”
A: “Aku, pun. Awalnya aku juga ketakutan untuk ditanyai. Tapi kadang ketika diskusinya asyik sekali, aku jadi ingin bertanya ke presenter. Jujur, aku memang tidak terlalu memikirkan apakah mereka bisa menjawab atau tidak. Kadang-kadang pertanyaanku betul-betul spontan. Cuma, aku yakin bahwa dosen pasti akan terlibat dan membantu. Aku ingin belajar. Aku ingin tahu dan kadang tidak bisa menahan hasratku yang menggebu untuk tahu.”
Z: “Ya, tanya dong kalau begitu. Itu hak kamu sebagai mahasiswa.”
A: “Hmm, mungkin yang harus kamu sadari, kita semua besar dengan budaya yang berbeda-beda.”
Z: “Maksudmu?”
A: “Ambil contoh, kamu. Separuh hidupmu kamu habiskan di ibukota. Dua pertiga sisanya kamu habisakan di luar negara ini, termasuk dalam momen-momen krusial yang membentuk budaya belajar: sekolah dasar, S1, dan S2. Kamu besar bersama orang-orang yang tidak takut bertanya, tidak malu menjawab. Tidak semua orang diberkahi dengan kepercayan diri seperti ini.
Aku contohnya, sebagian darahku adalah darah mereka yang dituntut percaya diri, cenderung cuek dengan rasa malu. Separuhnya lagi adalah berasal dari budaya yang erat mengajarkan unggah-ungguh, tepa selira, rendah hati bahkan cenderung rendah diri, serta sebisa mungkin menghindari keributan.
Aku hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya sepanjang usiaku, dan aku menyaksikan betul ragam ini.
Untungnya, atau sialnya, aku memilih karir yang mewajibkan aku untuk percaya diri dan berani bertanya. Selama aku menjadi wartawan, aku rasa aku underperformed soal keberanian untuk bertanya ini. Tetapi, lima tahun waktu yang tidak sebentar, dan mau tidak mau aku menyerap budayanya. Rasa penasaranku dan keberanianku terasah dengan sendirinya.”
Z: “Sekali lagi, kamu punya hak untuk bertanya. Apalagi kalau yang kamu kejar memang ilmu dan bukan nilainya. Mungkin mereka belum tahu rasanya bagaimana berusaha sebaik yang kita bisa adalah tuntutan di usia kita sekarang.”
A: “Aku ingin berpikir bahwa batasan usia tidak ada sangkut pautnya. Banyak kawan yang aku temui di sini, lebih bijaksana dari aku yang sudah tidak sepantaran dengan mereka. Tapi terus terang, aku mulai berpikir, mungkin memang itu bagian dari permasalahan. Di usia segini, aku ingin berusaha sebaik yang aku bisa. Aku juga punya tekad pribadi untuk memulai kembali dan memperbaiki hidupku yang sempat berantakan.
Masalahnya adalah, bagi sebagian orang — dengan rentang usia, pengalaman, dan budaya yang berbeda denganku — aku menjadi terlalu intimidatif di kelas. Baru-baru ini temanku bilang, aku berada di liga yang berbeda dan orang-orang merasa tidak nyaman. Lucu juga, padahal aku selalu minder dan menganggap mereka semua keren.”
Z: “Aku rasa, ini ada kaitannya dengan sistem. Highschool students, college students, university students… but by the end of the day, they are all students. But here, we call them mahasiswa. Maha dari segala siswa. Aku lihat bagaimana kalian diharapkan tidak hanya membaca, tapi juga harus merangkum dan mempresentasikannya. Entah kalian tidak dipercaya atau diharapkan bisa semuanya. Masalah tanya-jawab ini pasti ada kaitannya dengan grading system-nya, ya?” (Zaki memang keminggris anaknya, mohon abaikan.)
A: “Aku rasa begitu. Sedihnya, di sebagian mata kuliah, kemampuan kita menjawab juga dinilai. Belum lagi komentar-komentar dosen ketika kita tidak mampu menjawab. Mungkin itu akar dari semua ini. Yang jelas, aku sedih bahwa hasratku yang menggebu untuk ingin tahu hal baru disalahartikan oleh orang lain. Tapi, jika kita berada di sebuah lingkungan dan kita tidak bisa mengubahnya, ya kita harus menyesuaikan.”
Z: “Bukannya itu menyedihkan?”
A: “Sekali lagi, itu sudut pandangmu yang besar dengan cara yang berbeda denganku. Mungkin.”
Z: “Kamu hilang semangat, ya?”
A: “Iya, tapi aku yakin aku bisa mengatasinya. Terima kasih telah mengingatkan bahwa esensi kelas adalah untuk belajar. At least, I’ll stick to that :)”
—

Setelah 1000 kata lebih, aku tidak tahu harus menutup tulisan ini dengan apa, haha.
Intinya di sini, aku ingin berdialog (atau jatuhnya jadi bermonolog) dan melakukan refleksi sebagai ‘mahasiswa tua’ yang tengah berkuliah. Atau mungkin, tulisan ini adalah pembenaran atas ego-ku sendiri.
Nah, beberapa hari lalu aku menemukan cuitan yang bisa mewakili apa yang ingin aku sampaikan di sini. Aku lupa cuitan siapa yang aku baca. Ketika aku cari, banyak yang posting kata-kata yang sama. Kurang lebih, bunyinya begini:
Normalize saying “I don’t know enough to have an opinion.”
Karena aku sudah tidak tahu mau menulis apa lagi, sebagai penutup: Selamat Hari Pendidikan Nasional!
Harapanku, suatu hari nanti, sistem pendidikan kita bisa membuat orang-orang nyaman dan lebih terbuka dengan tradisi diskusi alih-alih debat, dengan kejujuran ketika kita tidak bisa menjawab dan beropini, dan dengan semangat mengejar ilmu dan bukan hanya nilai. Mungkin kalau sudah begitu, aku, kamu, siapapun, tidak akan lagi takut untuk bertanya atau ditanyai 🙂

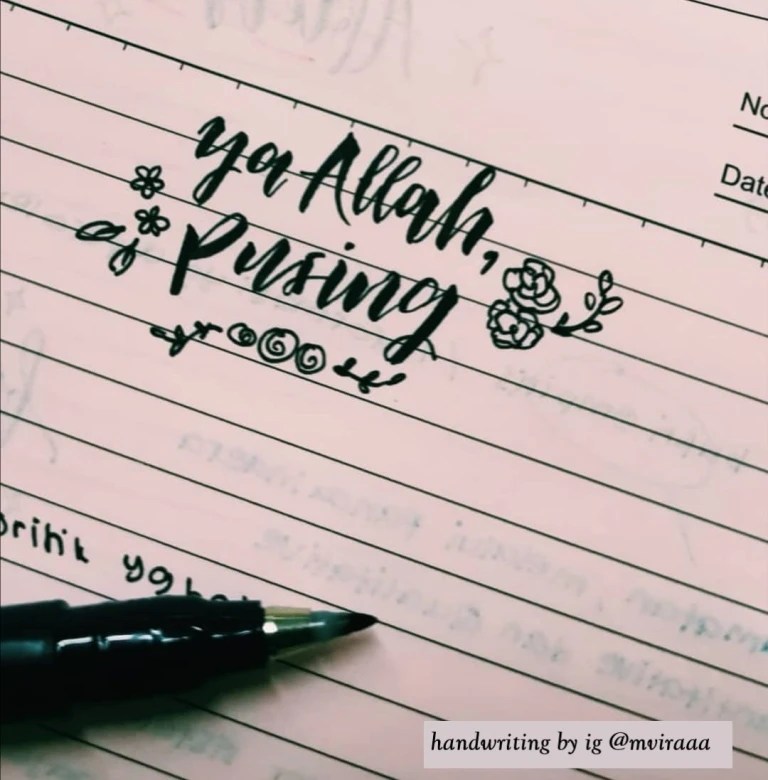
Leave a comment